Agama dan Takhayul
Agama yang dianut oleh suku Tengger merupakan perpaduan antara konsep Hindu dan Islam, yang mengizinkan pemujaan terhadap Trinitas (Brama, Wisnu, dan Siwa) bersama dengan pemujaan berbagai dewa dan roh, dan dengan kepercayaan pada satu dewa tertinggi.
Karena setiap kejadian, setiap tindakan di masa lalu, sekarang dan masa depan, juga setiap ruang-waktu hari, bulan, minggu, lingkaran tahun, kurang lebih terkait dengan dewa tertinggi — tiga dewa, dewa dan roh khusus. yang menyebabkan peristiwa, memimpin, mendominasi, menjadikan suku Tengger, betapapun sederhana dan sadar dalam hal ini, telah menjadi terbiasa dengan simbolisme agama yang diperlukan untuk menunjukkan tempat tinggal, kekuatan, tindakan para dewa dan roh, simbolisme yang tidak hanya dalam bentuk doa, tetapi sering juga dalam kehidupan rumah dan pekerjaan.
Ada kemungkinan bahwa beberapa hal tentang ajaran Hindu tentang dewa-dewa, seperti yang dibawa ke para pendeta Tengger pertama Mamanggis, Lili, Jebing, dll, dalam bentuk adaptasi, telah dituangkan dalam naskah daun lontar. Raffles menyebutkan dalam bukunya ‘The History of Java’ buku Tengger “Panglawu”, yang konon diberikan kepadanya dan di mana agama Tengger dikatakan telah dijelaskan.
Dilihat dari kata Panglawu (=panglabuh, dari labuh = menuangkan sesaji ke dalam api), buku itu hanya berisi legenda pengorbanan kepada Bromo atau rincian layanan Bromo.
Dukun Ngadisari memiliki sebuah buku yang di dalamnya tertulis beberapa catatan tentang agama, yang menurut catatan trinitas Hindu sebagai Sang Hiyang Batara Guru, Sang Hiyang Batara Wisnu dan Sang Hiyang Batara Siwa disajikan. Namun di atas ketiganya disebut sebagai dewa tertinggi : Sang Hiyang Wisésa atau Sang Hiyang Tunggal.
Sang Hiyang Wisésa inilah, yang kemahakuasaannya digambarkan dalam legenda Manik-Maya dalam cerita bahwa ia pertama kali menghancurkan dirinya sendiri dan dalam periode dua ribu tahun pertama langit (Suralaya) dan bumi (Buwana), matahari (Suriya), dan menciptakan bulan (Candra), siang (Manik) dan malam (Maya), setelah itu ia melahirkan sembilan putra dan empat putri, yang putra-putranya di sini disebut : Batara Maha Déwa atau Batara Brama, Sang Hiyang Sambu, Sang Hiyang Kamajaya, Batara Wisnu, Batara Bayu, Sang Hiyang Prit Hanjala, Sang Hiyang Kuwéra, Batara Maha Yekti dan Batara Siwa, masing-masing melambangkan atau mengendalikan : titik mata angin, ruang waktu, warna. (1)
Menurut pandangan suku Tengger, Sang Hiyang Batara Guru bersemayam bersama dewa-dewa lain di tempat tinggal para dewa, di Suralaya, yang disebut Gunung Semeru.
Para dewa juga dikenal oleh para pendeta Tengger: Batara Suriya, Batara Sri Wehayu (Bayu), Batara Maha Déwa, Sang Hiyang Déwata, Sang Hiyang Mahisura (=lswara), Sang Hiyang Sukma, Déwa Raka, Sang Hiyang Puspapuja, Sang Hiyang Maha Meru.
Dalam bentuk doa, Sang Hiyang Puspapuja diwakili dengan Sang Hiyang Maha Meru di atasnya, sedangkan Sang Hiyang Sukma Dewata dianggap sebagai yang menjaga kehidupan manusia, menghargai detak jantung dan menembus ke dalam diri manusia melalui bukaan dari tubuh manusia.
Dari semua dewa, Sang Hiyang Batara Brama atau Sang Hiyang Batara Guru memiliki makna khusus, karena ia adalah dewa api, yang sebagai fenomena alam-kawah misteri telah menjadi bahan penghormatan khusus di antara pemikiran dan perasaan animistis suku Tengger selama tiga abad. Dia tidak selalu disebut dengan nama Brama ; ia digambarkan sebagai Sang Hiyang Geni Batara Suci yaitu Dewa Api, Dewa yang murni, atau Sang Hiyang Geni Sukma Adi, yaitu Dewa Api dengan jiwa yang murni. Bahkan api, yang muncul dari dan melaluinya, dan memiliki kekuatan untuk menghapus segala dosa, kadang-kadang tidak secara langsung disebut “Api Brama”, tetapi “Air”, yang tumbuh dari jantung atau paru-paru Brama.
1) Legenda Manik-Maya telah dibahas secara ekstensif dalam Manual Pengetahuan Sejarah, Geografi, Fabel, dan Aritmatika Waktu Jawa oleh J. Hageman J. Cz. 1852.
Selain itu, ada Tuhan, dewa, atau roh, yang berdiam di tempat-tempat tertentu di sekitar dan di dekat gunung berapi Bromo; Demikianlah Déwa Kusuma bersemayam di dalam kawah (2) Sunan Tenguk di tepi kawah atas, Sunan Perniti di tempat Bajangan, di kaki kerucut kawah, di mana tangga dibangun untuk wisatawan dimulai, Sunan Perniti ini disebut di Lumajang Tengger, Sunan Linggeng, disebut Sunan Pernata di Poten, di kaki Bromo, di Lautan Pasir.
Raden Dumeling di pintu gerbang Cemoro Lawang (Probolinggo Tengger), Kyai Omah dan Nyai Omah di pintu gerbang Mungal (Pasuruan Tengger). Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa, sehubungan dengan kekhidmatan besar pengorbanan ke Bromo, banyak dewa penjaga atau penjaga yang dipikirkan di sekitarnya, yang duduk tepat di tempat-tempat yang dipilih sedemikian rupa sehingga pemujaan dan tahap pemujaan dapat dilakukan sebagai wisata kurban, mulai dari turun gunung Cemoro Lawang dan gunung Mungal melewati Lautan Pasir, dilanjutkan dengan pendakian dinding kerucut bawah, pendakian dinding kawah atas, berdiri atau duduk berhadapan atau di atas pembukaan kawah, dan diakhiri dengan nglabuh, yaitu penuangan sesaji ke dalam api ilahi.
2) Van Herwerden menyebut dewa yang bersemayam di kawah: “Sunan Ibu”; Junghuhn memanggilnya: “Déwa Sunan Ibu”.
Kursi penjaga atau dewa penjaga itu adalah tahap suci dalam perjalanan pengorbanan ; para pendeta tidak turun ke Dasar sampai mereka memberi penghormatan kepada dewa khusus di celah gunung (1); dan di kaki gunung berapi kerucut para imam berkumpul dari segala penjuru berdoa sebelum naik kawah.
1) Hageman menyebut Celah Mungal dengan ciri – cara yang benar sehubungan dengan konsepsi orang Tengger – “Pintu gerbang gunung istana agung para dewa Tengger”.
Air juga memiliki dewa dan roh penjaga atau pelindung, yang memiliki tempat duduk di tempat yang berbeda ; Sang Kumur Putih menjaga air terjun, Sang Kumur Putih mata air besar, Gombang Putih Kyai Bureng dan Nini Bureng menjaga Babaggan, yaitu tempat orang datang ke air untuk mencuci atau mandi, Buto Cemer menjaga tempat-tempat yang dalam di sungai, Sang Ratu Kendal Putih mata air kecil. Di Pegunungan Probolinggo Tengger, Sang Kendal Putih adalah dewa penjaga yang duduk di air, Sang Buto Ijo adalah dewa yang menjaga babaggan, Sang Nabi Silumman, dewa yang menjaga pantai.
Lebih jauh, orang Tengger mengenal sangat banyak penjaga dan wali, pemelihara dan pelindung tubuh, harta benda dan peristiwa, roh, yang secara khusus disapa secara halus dalam doa ketika diminta berkah atas fakta atau tindakan tertentu yang dikendalikan atau dipimpin oleh roh-roh itu. Demikianlah orang mengenal Ibu Pertiwi (Ibu Bumi), Bapa Kasa (Bapak Langit), Kaki atau Nini Resajaga (Kakek atau Nenek, yang menjaga dan melindungi), Kaki atau Nini Panggih (Kakek atau Nenek, yang mengingat pertemuan antara mempelai pria dan wanita), Kaki atau Nini Among Tuwuh (Kakek atau Nenek, yang memelihara pertumbuhan), Kaki atau Nini Among Suka (Kakek atau Nenek, yang mengurusi hawa nafsu), Kaki atau Nini Among Raga (Kakek atau Nenek, yang mengurus tubuh ), Kaki atau Nini Among Sugih (Kakek atau Nenek, yang mengurus kekayaan), Kaki atau Nini Among Teguh (Kakek atau Nenek, yang memelihara ketabahan), Kaki atau Nini Among Tetep (Kakek atau Nenek, yang selalu menjaga) .
Yang sangat mencolok adalah bahwa roh-roh ini dianggap sebagai laki-laki dan juga perempuan, dan biasanya disapa dalam bentuk doa dengan sangat lembut dengan kaki dan nini; kadang-kadang bahkan sebelum nama-nama roh yang melindungi dan memelihara seseorang menempatkan gelar “Sang”, biasanya hanya digunakan untuk dewa (2).
Bahkan ada pelayan dan perawat para dewa; misalnya, seseorang berbicara tentang Kaki Among Purba Wisésa, Nini Among Guru, sedangkan setiap desa memiliki Dèwata (dewa) sebagai santo pelindung (Batur).
2) Dalam esainya, “Nini Towong” (Tijdschr. voor Ind. TL and Uk. vol XLIII 1901), Dr. G.A.J. Hazeu: “Nini, seperti kaki, adalah ungkapan umum untuk roh; banyak mantera dimulai dengan “Kaki N.N.”, “Nini N.N.” Apakah arti asli dari “kakek, nenek” yang masih hidup dalam hal ini, atau apakah itu hanya berarti “Tuan, Nyonya” (arti ini memiliki (ka)ki dan (ni)ni sama), tidak bisa dibedakan.
Sebagian besar kata yang menunjukkan kerabat yang lebih tua digunakan atau juga digunakan sebagai kata sapaan yang sopan, baik kepada yang muda maupun yang lebih tua. Adapun “Nini” khususnya, lihat Jav. wdbk. dan Kawi Balin. Wdbk, Jenis Bahasa Wahlbeem hal. 246 dan lih. juga sambutan umum Prof Kern dalam Bijdr. Kon. Instit. VI, VI p. 102.
“Sang” adalah KI dari si; itu selalu mengungkapkan kekaguman dan rasa hormat yang tinggi. Juga, ‘Nini’ ‘ itu sopan, tetapi ada kehalusan di dalamnya; itu mengungkapkan hubungan yang lebih intim.” Dan selanjutnya: Dalam pelayanan leluhur, pada umumnya semua dewa atau roh disapa sebagai ayah atau ibu, lebih-lebih sebagai kakek atau nenek; karena mereka awalnya diperkirakan tidak berbeda dengan roh “Nenek”, yang berkembang menjadi “Nenek Moyang”.
Selain Tuhan dan para dewa, penjaga dan pelindung yang baik atau roh yang memelihara orang Tengger mengenal roh jahat “Banaspati”, yang menjaga atau melindungi barang antik atau perbatasan desa dan disebut misalnya Kyai dan Nyai Tugu Banaspati. Banaspati ini sebenarnya bukan roh jahat, tetapi hanya mungkin dianggap sebagai setan, karena dimaksudkan untuk menakut-nakuti atau mengintimidasi siapa pun atau apa pun yang melakukan kejahatan terhadap apa yang dipercayakan kepada penjaganya.
Roh-roh jahat juga ada dalam kepercayaan suku Tengger, tetapi tidak disebutkan. Mereka dapat disimpulkan, dan ini dilakukan dengan menempelkan tanda dan gambar di pintu tempat tinggal, seperti, misalnya salib, menunjukkan persimpangan jalan, yang dengannya roh-roh jahat disesatkan, atau sosok manusia, untuk memberikan kepada roh-roh jahat, untuk menjelaskan kepada roh-roh bahwa penghuni rumah itu terjaga dan waspada.
Semua roh penjaga desa yang baik disebut dengan nama umum “Baureksa”; mereka menempati tempat yang agak menonjol dalam kepercayaan suku Tengger. Selain itu, setiap desa memiliki Cakal bakal atau akal bakal, pendiri atau penggarap pertamanya (sing Truko), yang dihormati dan dikenang sebagai leluhur dan beberapa di antaranya memiliki kekuatan gaib khusus.
Sebagai nenek moyang, Kyai dan Nyai Gedé Dadappputih dipuja oleh masyarakat Tengger, sedangkan yang kurang lebih melegenda antara lain Kyai Omah dan Kyai Teger, Putri Tatiban, disebut juga Nyai Omah, Nyai Anteng atau Nyai Teng, Setiyo dan Tuhu dari legenda Aji Saka .
Cakal-bakal atau akal-bakal umumnya dikenal dengan nama ; itulah nama pendiri pertama desa Ngadiwono, Kyai dan Nyai Ranten; pendiri pertama desa Nongkojajar (Wanasari), Blarang dan Sumberpitu masing-masing bernama Kyai Singobromo, Kyai Lasimin dan Kyai Dèmpok.
Pemujaan terhadap leluhur terbentang cukup jauh; tanah di mana penggarap desa telah tinggal dianggap tanah kudus atau suci. Suku Tengger menganggap diri mereka sebagai anak dan cucu (anak putu) dari nenek moyang. Ketika gambar jiwa diperlukan untuk upacara, mereka dibuat tidak hanya dari dewa dan dewa dan kerabat yang baru saja meninggal, tetapi juga dari leluhur.
Kehidupan manusia diurus oleh Sang Hiyang Sukma Déwata (lihat di atas); representasi yang lebih populer dari kepedulian terhadap kehidupan manusia adalah yang dilakukan oleh Kaki dan Nini Among Tuwuh (harfiah: Kakek Kecil dan Nenek Kecil, yang merawat
pertumbuhan).
Tubuh manusia dianggap oleh orang Tengger sebagai sarung material jiwa, dan diibaratkan sebagai pembungkus (Selaga) sekuntum bunga ; jiwa adalah yang halus, yang rapuh (Juwita), yang tidak dapat binasa (Langgeng), yang benar dan yang sejati (Pramana). Ketika seorang pria meninggal, tubuhnya kembali ke Ibu Pertiwi, dewa bumi, dan diterima, menurut ide-ide agama yang baik, pertama oleh pengawal (Sing Magersari) dari dewi yang menjaga kuburan. Jiwa dibayangkan terjebak atau dipenjarakan dalam tubuh manusia yang hidup; jika manusia mati, maka jiwa “Dibebaskan” oleh dewa tertinggi, di mana selubung materi “diletakkan untuk kebaikan”.
Sebelum jenazah dikuburkan, orang-orang memohon agar jenazahnya dibersihkan sepenuhnya dengan air dari surga. Pembersihan ini dianggap sebagai upacara, di mana, seperti halnya dengan memandikan mayat, banyak yang bermanfaat; ‘demikianlah dewa mengambil air; seorang malaikat akan mengundang tubuh sebagai tamu ; malaikat lain akan membimbingnya ; malaikat ketiga akan memandikannya.
Representasi ini dengan jelas mengingat pengaruh Islam dalam kaitannya dengan ritus memandikan jenazah di kalangan Muhammad. Demikian pula, gagasan bahwa jembatan sirattal membentuk transisi ke alam kematian diambil dari konsep islam. Juga didoakan agar tubuh yang tak berjiwa itu, agar dalam perjalanannya ke Ibu Pertiwi tidak tersandung, tidak mendengar kata-kata jahat, sehingga dapat diterima dalam ketenangan dan kemurnian yang sempurna oleh dewi bumi.
Saya menganggap gagasan Tengger lebih kuno dan karena itu orisinal bahwa, jika jiwa ingin disucikan, tidak ada yang tersisa dari penutup material, mayat ; itu harus benar-benar binasa ; itulah sebabnya imam juga membuat doa simbolis dalam kematian agar yang mati, tubuh yang tidak berharga digantung di pohon, kepala mayat diikat di suatu tempat dan tulang-tulangnya dihancurkan sampai “nyunyur dadi awu”, jadi benar-benar hancur dan berubah menjadi debu, dll.
Jiwa mengalami proses penyucian di naraka atau api penyucian, di mana ia terapung dengan gelisah tanpa titik tumpu yang tetap. Cahaya, api, dan air, yang datang dari Timur, akan melenyapkan semua kejahatan yang telah dialami jiwa sebelumnya dalam selubung material dan yang dapat menghalangi pemurnian. Bagaimana jiwa dimuliakan terbukti dari fakta bahwa dalam doa imam untuk keselamatannya dia disebut Kaki dan Nini Hiyang Sukma yang penuh hormat, sehingga dibandingkan dengan dewa.
Neraka, menurut gambaran religius, terdiri dari beberapa bagian; Terakhir, jiwa terapung di “Kawah Condromuko”, yang merupakan bagian timur neraka, yang darinya dibawa oleh kekuatan doa imam dan dengan bantuan utusan Sang Hiyang Wisésa, untuk pergi ke Suwarga atau surga. (Api naraka direpresentasikan sebagai “Api Putih” Sang Hiyang Wisésa). Ini terjadi pada hari ke seribu setelah kematian seseorang, pada kesempatan pesta pengorbanan yang kemudian diberikan. Untuk tujuan ini jiwa pertama-tama dipanggil kembali ke rumah dengan bentuk doa tertentu, setelah itu dibayangkan bahwa itu ada dalam gambar jiwa yang disiapkan sebelumnya, yang diperlakukan dengan hormat. Gambar-gambar jiwa ditempatkan — karena biasanya ada beberapa yang dibuat untuk jiwa orang-orang yang berbeda — di atas bantal-bantal yang dilapisi dengan baik dalam warna putih, di mana mereka dapat dilihat oleh semua orang; mereka diperlakukan dengan cinta anak-anak untuk orang tua, dengan kegembiraan tuan rumah di hadapan tamu-tamu terkenal, dengan kebajikan, kebaikan, kerendahan hati, dan kealamian yang dengannya seseorang memenuhi keinginan kerabat. sembah yang rendah hati dibuat untuk gambar jiwa.
Namun gagasan tentang kegelisahan jiwa yang melayang-layang di dalam naraka tetap dan tidak berubah; Lagi pula, dalam salah satu bentuk doa permintaan dibuat, agar jiwa mendapat pijakan yang kokoh di deretan 100 duit (sesaji yang sama) dan diikat dengan gulungan benang kapas (juga sesaji), sehingga mudah baginya, melewati neraka ke suwarga. Untuk pembebasan itu, penebusan (ngentas, mengeluarkannya dari api) diperlukan berbagai tindakan simbolis, yang diakhiri dengan pembakaran gambar-gambar jiwa, yang dilakukan dengan penuh hormat dari rumah dan bertabur bunga.
L.H.W. Baron van Aylva Rengers, yang atas ‘buku hariannya yang tidak diterbitkan’ (Sumbangsih bagi pengetahuan koloni Belanda dan asing. 1846. hlm. 412 dst) tentang tata krama dan adat istiadat suku Tengger mendapat informasi dari H.J. Domis, Residen Pasuruan di waktu itu, ternyata salah paham atau salah memahami apa yang disampaikan kepadanya dan membuat kesalahan dalam buku hariannya dengan menyatakan bahwa suku Tengger percaya akan keluarnya jiwa dari orang baik ke dalam tubuh anak pertama yang lahir dalam keluarga, dari apa perpindahan jiwa orang Tengger akan diyakinkan jika anak yang mulai rewel dan menangis, tenang dan diam begitu satu-satunya benda milik almarhum diperlihatkan.
Orang Tengger tidak percaya dengan perpindahan jiwa seperti itu. Memang benar, menurut pemikirannya, ada roh jahat yang menyebabkan penyakit (termasuk pada anak-anak) dan dapat diusir dengan “nyuwuk” (mantera tertentu) dan dengan membuat tanda atau gambar dengan kapur. Ada juga jiwa jahat (Ki dan Ni Duratma), jiwa yang melayang di angkasa (sukma awang – awang), jiwa yang melayang di ruang hampa (sukma uwung-uwung). Tetapi perpindahan jiwa tertentu tidak diketahui oleh suku Tengger.
Dalam agama Tengger, Suwarga atau surga, yang dilalui oleh arwah yang disucikan, dibedakan dari Suralaya, atau tempat tinggal para dewa. Islam juga dengan jelas meninggalkan jejaknya pada gambar-gambar surga. Misalnya, seseorang berbicara tentang surga sebagai kramat Allah (pengucapan: kramattulah), di mana 144 widadari atau bidadari berada.
Dalam bentuk doa tunggal yang digunakan hanya di wilayah wilayah Tengger, di mana agama Islam paling kuat merambah penduduk, masih ada jejak lama agama Budha yang dapat ditemukan; karena di dalamnya dibuat representasi dari tempat tinggal para dewa, di mana Sang Budha bersemayam, “bersinar, seperti cahaya keemasan bulan.”
Pengaruh Islam terhadap agama Tengger, bagaimanapun, sedemikian rupa sehingga Sang Hijang Wisesa sebagai dewa tertinggi sangat mudah ditempatkan di samping Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Dalam bentuk doa (terutama digunakan di Probolinggo Tengger) Mohammad bahkan disebutkan, kata ‘wali’ sering digunakan dan bahkan membentuk ‘kalimah loro’ (la ilaha illallah, wa Muhammad rasul Allah) yang terkenal dalam salam.
Tetapi penyisipan konsep agama asing ini (mungkin atas desakan Islam atau karena sopan santun terhadap kepala dan imam Muhammad) berlangsung sedemikian rupa sehingga agama Hindu tetap dikedepankan, dan dari sudut pandang Islam konsepsi agama yang kurang baik, yang diberikan Allah.
Ketika mempelai laki-laki muda membuat pengakuannya, dia menyatakan bahwa dia percaya kepada Allah dan Muhammad, namun dia menambahkan bahwa bayangan Muhammad adalah seorang laki-laki, sama seperti, menurut mistisisme Hindunya sendiri, dari Brahma dapat menciptakan manusia.
Jadi yang dia maksud adalah kata Arab “Qiblat” (yang bagi Muslim sejati hanya ada satu, yaitu arah Mekah); dia tidak, bagaimanapun, mengucapkan kata dalam bahasa Jawa, “kiblat” atau “keblat,” tetapi sangat biasanya mengubahnya menjadi “kabelat” dan, terlebih lagi, mengatakan bahwa ada empat di mana makhluk ilahi terlihat. Juga dari bentuk doa lain, orang memperhatikan bahwa pikiran Allah sangat salah sehingga namanya mengarah pada permainan kata-kata: Illulah, Marullah, Barullah, Gantungngullah.
Seseorang mendapat kesan bahwa semua ini dilakukan dengan desain yang bagus; namun, pencampuran dengan Islam sebagian besar harus dikaitkan dengan kemampuan beradaptasi orang Tengger yang baik hati. Telah dijelaskan kepada saya oleh seorang dukun bahwa doa dan bentuk-bentuk lain hanya dianggap sebagai cara (bentuk luar orang bijak), dari mana dapat disimpulkan bahwa orang Tengger pada zaman dahulu mempercayai dewa dan roh mereka, meskipun kebajikan agama yang dilaksanakan, namun tidak berarti menyerah.
Sangat mengejutkan bahwa percampuran dengan Islam juga terjadi dengan cara yang sama naifnya di antara kelompok suku lain yang tetap terisolasi, Badui di Banten.
Dr. Jul. Jacobs dan J.J. Meijer menulis dalam karya mereka: The Badoej’s, sehubungan dengan itu : Apakah ini adalah hasil dari pengaruh islam, atau apakah mereka benar-benar melihat dewa penganiaya mereka yang perkasa, dewa yang tinggi, atau demi suku Muhammad mereka , atau karena takut pada tetangga mereka, begitu banyak yang pasti: Mereka telah menetapkan bagian tertentu, bahkan signifikan dalam jajaran mereka kepada Allah kaum Muhammad dan kepada Muhammad sendiri.” (1)
Konsepsi orang Tengger tentang kesucian dewa-dewa dan roh-rohnya adalah bahwa ini tidak boleh direpresentasikan dengan cara yang duniawi; dengan demikian Wayang Purwa dilarang di kalangan suku Tengger, karena di dalamnya disebut dan ditampilkan Poro Sepuh (orang dahulu, di antaranya juga dewa dan arwah). Orang Tengger percaya bahwa dengan memberikan gambaran seperti itu suatu bencana akan datang ke daratan dan orang-orang, orang-orang akan diserang oleh harimau (ini tentu saja contoh pandangan kuno, karena sekarang tidak ada lagi harimau di Pegunungan Tengger), angin kencang akan merusak tanaman, dll.
1) Orang Badui juga mengenal sebagai dewa tertinggi Batara Tunggal, yang dapat disamakan dengan Sang Hijang Wisésa di suku Tengger.
Sungguh luar biasa bahwa permainan wayang juga dilarang di Kuningan pada waktu itu (lihat artikel: Takhayul Orang Sunda oleh FG Wilsen dalam Tijdschr. voor Ind. TL dan VK. Nieuwe serie bagian I. 1855); dan di sana juga diyakini bahwa dengan menampilkan wayang akan selalu ada kecelakaan dan seseorang akan kehilangan nyawanya. Bahkan Badui yang hidup sangat sederhana dan keras tidak menunjukkan permainan wayang.
Setiap desa di Tengger memiliki apa yang disebut Pedanyangan atau tempat tinggal para Danyang (roh); beberapa desa bahkan memiliki dua; pedanyangan ini biasanya potongan-potongan kecil dari sisa hutan kayu liar atau cemara. Selain pedanyangan, desa juga memiliki sanggar umum atau tempat persembahan, di mana, misalnya, setiap 5 tahun sekali diadakan festival besar “Unan-unan” untuk kepentingan desa, di mana biasanya seekor lembu atau kerbau disembelih.
Sanggar, tempat persembahan disimpan, ada di rumah setiap dukun; sepotong loteng biasanya digunakan untuk ini. Sanggar Pamelengan (Pameleng = doa yang sungguh-sungguh dan khusyuk) adalah sanggar rumah, tempat bersemayamnya dewa dan roh, dan tempat kurban yang ditujukan untuk mereka juga disimpan sementara. Sanggar di rumah dukun Tosari disebut “Sanggar Agung”.
Sanggar rumah untuk upacara kurban tidak selalu di rumah dukun; di desa Mororejo misalnya, sanggar umum seharusnya menjadi rumah petani “Pak Siah”, di mana pengorbanan umum selalu dilakukan.
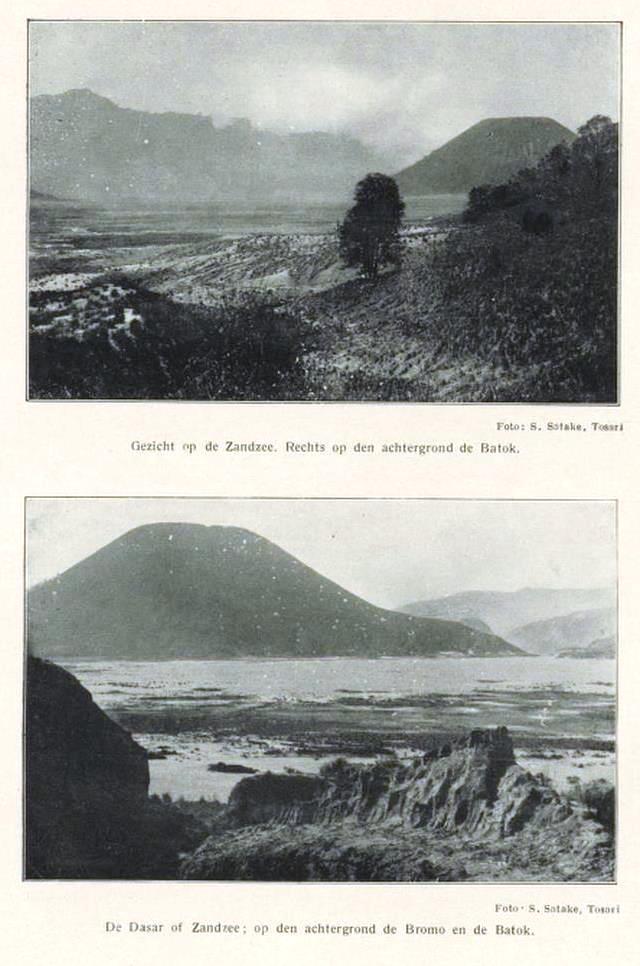
Sumber : Buku “Tengger En De Tenggereezen” Karya J. E. Jesper (Resident Van Jogjakarta), Circa 1928.
Postingan Terkait :
Tengger dan Suku Tengger (Kata Pengantar)
Tengger dan Suku Tengger (Bab I)

